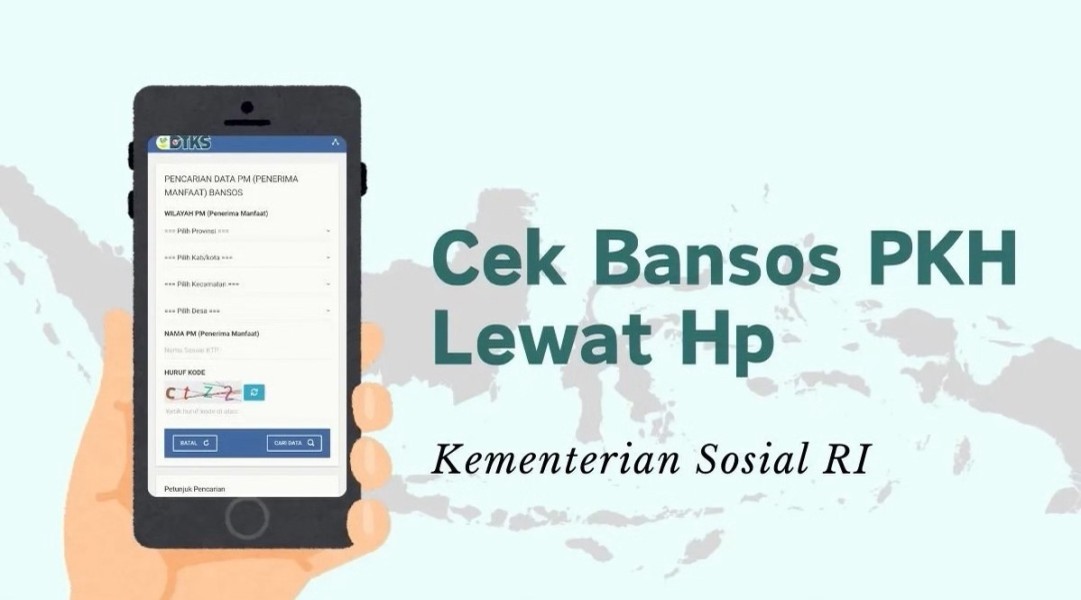JAKARTA - Sekolah bukan sekadar ruang belajar formal, melainkan ladang tempat nilai-nilai kehidupan ditanamkan. Namun, seiring maraknya kasus perundungan, rendahnya empati, dan menipisnya sopan santun, muncul pertanyaan besar: sudahkah lembaga pendidikan kita berhasil membentuk manusia seutuhnya? Realita hari ini justru menunjukkan bahwa banyak sekolah belum sungguh-sungguh menjalankan fungsinya sebagai pengasuh karakter peserta didik.
Fenomena ini tercermin dalam sejumlah kasus yang mencuat ke publik. Salah satu yang paling menghebohkan terjadi pada Juli 2025, ketika dua remaja di Depok melakukan perundungan terhadap temannya secara brutal dan menyiarkannya langsung melalui media sosial, sebagaimana dilaporkan oleh Detik.com dalam berita berjudul "Viral 2 Remaja di Depok Bully Teman Sambil Live IG, Ortu Korban Lapor Polisi." Korban dipukul, dijambak, bahkan dilempari benda keras tanpa ada rasa iba dari pelaku.
Beberapa bulan sebelumnya, peristiwa serupa terjadi di Cirebon. Seorang siswa SMP menjadi korban pengeroyokan di dalam kelas, disaksikan oleh teman-teman yang justru memilih merekam video ketimbang melerai. Kedua kasus ini menunjukkan betapa nilai-nilai dasar seperti empati dan solidaritas makin memudar di lingkungan sekolah.
Situasi ini menjadi sinyal kuat bahwa pendidikan karakter harus kembali menjadi fokus utama sistem pendidikan nasional. Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) bukan sekadar program tambahan, tetapi semestinya menjadi jantung dari proses belajar-mengajar.
Lima Pilar Pendidikan Karakter: Rangka Bangun Budaya Sekolah
Dalam manajemen pendidikan, pendidikan karakter ditopang oleh lima elemen kunci yang saling terkait. Tanpa perencanaan dan pelaksanaan yang matang, nilai-nilai karakter hanya akan menjadi slogan tanpa makna.
1. Perencanaan yang Visioner
Menurut Kauffman (dalam Soemantri, 2014), tahap awal PPK dimulai dari perencanaan yang matang, meliputi penentuan tujuan hingga pemanfaatan sumber daya. Robbins dan Coulter membaginya menjadi dua jenis: rencana formal yang wajib dijalankan semua elemen sekolah dan rencana informal yang lebih fleksibel.
Hayes (2003) menegaskan pentingnya partisipasi komunitas sekolah dalam merumuskan nilai-nilai yang akan ditanamkan. Sementara Bulach (2002) mengingatkan agar kurikulum disusun dengan mempertimbangkan nilai-nilai masyarakat dan harapan orang tua.
Permendikbud No. 20 Tahun 2018 merumuskan lima nilai utama yang harus ditanamkan, yakni religius, nasionalisme, kemandirian, integritas, dan gotong royong.
2. Pengorganisasian yang Inklusif
Budaya sekolah tidak bisa dibentuk oleh satu pihak saja. Kepala sekolah, guru, siswa, bahkan komite sekolah dan masyarakat sekitar harus dilibatkan secara aktif.
Kepala sekolah berperan sebagai pembuat arah kebijakan, guru sebagai teladan harian, siswa sebagai pelaku utama, dan organisasi seperti OSIS serta Pramuka sebagai media pembiasaan nilai. Semua pihak perlu berjalan seirama agar karakter benar-benar tumbuh dalam keseharian.
3. Pelaksanaan yang Sistemik
Terry (2012) menyebut pelaksanaan sebagai proses menggerakkan seluruh anggota organisasi. Nawawi dan Martini (2005) menambahkan bahwa pelaksanaan mencakup pengarahan dan pemanfaatan sumber daya manusia secara optimal.
Dalam konteks PPK, pelaksanaan mencakup aktivitas sederhana namun berdampak, seperti salam pagi, menjaga kebersihan kelas, menghormati guru, hingga kegiatan literasi dan seni. Nilai seperti tanggung jawab dan kerja keras bukan hanya diajarkan, tapi dibudayakan melalui praktik harian.
Tarmansyah dkk (2012) menyebutkan bahwa keberhasilan pelaksanaan PPK bergantung pada kebijakan yang mendukung, kompetensi guru, dan keterlibatan masyarakat.
4. Pengawasan yang Membina
Pengawasan dalam pendidikan karakter harus bersifat membina, bukan menghukum. Guru, kepala sekolah, dan komite perlu melakukan pemantauan rutin untuk melihat sejauh mana nilai-nilai karakter sudah terinternalisasi.
Proses ini dilakukan melalui refleksi, observasi, serta diskusi. Tujuannya bukan sekadar menilai, tetapi membantu siswa tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik.
5. Evaluasi yang Reflektif dan Komprehensif
Arikunto (1988) menyebut evaluasi sebagai proses penting dalam mengetahui capaian pendidikan. Bloom menekankan pentingnya pengumpulan data secara sistematis, sementara Koesoema (dalam Zahri Harun, 2013) menjelaskan bahwa evaluasi karakter mencakup aspek program, struktur, personal, dan komunitas.
Kemendiknas (2011) menyebutkan berbagai metode evaluasi seperti observasi, penilaian antarteman, jurnal, hingga portofolio. Gunawan (2012) juga menekankan perlunya evaluasi berbasis nilai dan kolaborasi semua pemangku kepentingan.
Budaya Sekolah: Tanah Subur bagi Nilai Karakter
Pendidikan karakter tidak bisa tumbuh di ruang hampa. Ia harus berakar pada budaya sekolah yang hidup—dari cara guru menyapa murid, cara siswa memperlakukan temannya, hingga suasana kelas yang mengedepankan saling menghormati.
Deal dan Peterson (2009) menjelaskan bahwa budaya sekolah terbentuk dari nilai-nilai dan tradisi yang hidup di tengah komunitas. Edgar Schein (2010) bahkan menyebut budaya sekolah sebagai sistem nilai bawah sadar yang memengaruhi perilaku warga sekolah setiap hari.
Purkey dan Novak (1996) menambahkan bahwa sekolah yang memiliki “budaya mengundang” akan menciptakan iklim pembelajaran yang sehat, positif, dan partisipatif.
Pendidikan Karakter adalah Inti, Bukan Tambahan
Di tengah dunia yang makin kompleks dan nilai-nilai yang sering tergerus zaman, pendidikan karakter harus kembali ke panggung utama. Bukan sebagai program sesaat, melainkan sebagai fondasi pendidikan yang sejati.
Guru dan kepala sekolah berperan sebagai agen perubahan yang nyata, orang tua menjadi mitra sejajar dalam pembentukan karakter, sementara siswa menjadi pusat dari proses transformasi itu sendiri.
Karakter yang kuat tidak dibentuk dalam sehari, melainkan melalui keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah yang konsisten. Dan semua itu, hanya bisa terwujud jika sekolah kembali ke akar: mendidik manusia secara utuh, bukan hanya mencetak lulusan dengan nilai tinggi.