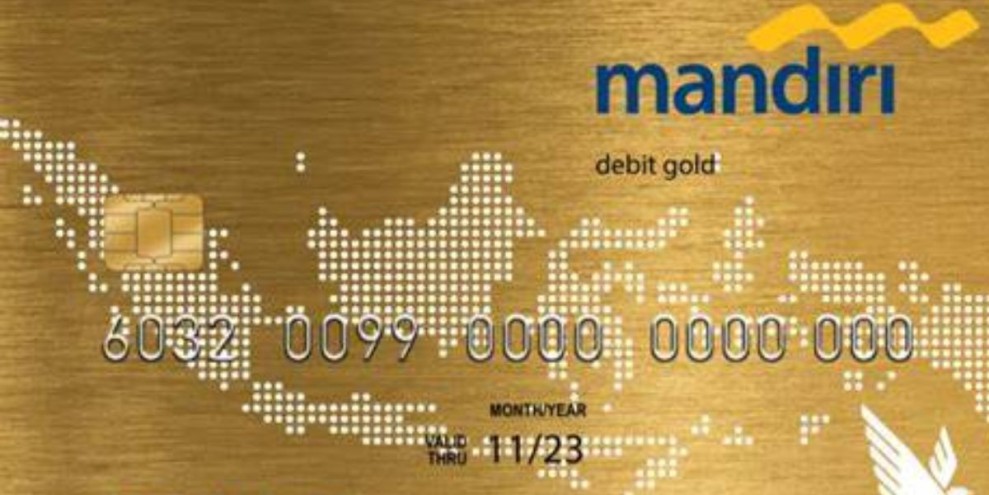JAKARTA - Indonesia terus berupaya mencapai target Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060 melalui berbagai inisiatif, termasuk percepatan adopsi kendaraan listrik dan pemanfaatan energi terbarukan seperti tenaga surya. Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Peraturan Presiden No.55/2019 yang kemudian direvisi melalui Peraturan Presiden No.79/2023 untuk mendukung pertumbuhan kendaraan listrik di tanah air. Data dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menunjukkan lonjakan penjualan mobil listrik nasional sebesar 684 persen pada Januari 2024 dibandingkan tahun sebelumnya, mencapai 2.335 unit.
Namun, di balik ambisi tersebut, muncul tantangan signifikan terkait pengelolaan limbah yang dihasilkan dari teknologi energi hijau. Salah satu perhatian utama adalah pengelolaan limbah baterai kendaraan listrik yang dapat mencemari lingkungan jika tidak ditangani dengan baik. Pemerintah menargetkan jutaan kendaraan listrik beroperasi pada tahun 2030, yang berarti potensi limbah baterai akan meningkat secara signifikan. Menurut laporan Antara News, pengelolaan limbah baterai menjadi krusial dalam mendukung transisi energi bersih di Indonesia.
Selain itu, pengolahan sampah menjadi energi listrik melalui teknologi Waste-to-Energy (WtE) juga menghadapi berbagai tantangan. Penerapan teknologi WtE di Indonesia, seperti proyek Tempat Pengolahan Akhir Sampah (TPAS) Legok Nangka, menawarkan solusi inovatif untuk pengelolaan sampah berkelanjutan sekaligus menghasilkan energi. Namun, skema Feed-in Tariff (FiT) yang dijamin dalam Perpres No. 35/2018 menimbulkan risiko finansial terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurut kajian Kementerian Keuangan, implementasi WtE memerlukan reformasi sistemik di berbagai aspek pengelolaan sampah, termasuk pembiayaan, kelembagaan, regulasi, teknis, dan sosial budaya.
Di sektor industri, pemanfaatan limbah sebagai sumber energi juga menjadi fokus. Perusahaan seperti APRIL Group di Riau telah memanfaatkan sludge, limbah dari pengolahan air limbah, untuk digunakan kembali sebagai sumber energi dalam operasional pabrik. Langkah ini menunjukkan bahwa di balik tantangan pengelolaan limbah, terdapat peluang besar untuk mengubah limbah menjadi sumber daya bernilai.
Kementerian Perindustrian juga memetakan sejumlah industri yang dapat memanfaatkan biomassa dan bahan bakar alternatif dari sampah melalui teknologi Refuse Derived Fuel (RDF). Industri yang dimaksud mencakup semen, pulp & kertas, besi dan baja, serta plastik. Penelaah Teknis Kebijakan Kementerian Perindustrian, Fausan Arif Darmadli, menyatakan bahwa potensi permintaan RDF pada hilir industri sangat besar, namun keberhasilannya bergantung pada koneksi antara penyedia dan industri sebagai offtaker.
Namun, transisi menuju energi hijau di Indonesia tidak lepas dari tantangan besar, terutama ketergantungan yang mendalam pada bahan bakar fosil. Indonesia adalah salah satu produsen batu bara terbesar di dunia, dan bahan bakar ini masih memainkan peran penting dalam pembangkit listrik nasional. Menurut data dari Kementerian ESDM, sekitar 60% listrik di Indonesia masih dihasilkan dari batu bara. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya menuju energi hijau, ketergantungan pada bahan bakar fosil masih menjadi hambatan signifikan.
Selain itu, pengelolaan limbah plastik juga menjadi tantangan dalam revolusi hijau. Pertumbuhan populasi dan urbanisasi menyebabkan peningkatan jumlah sampah, yang menimbulkan tekanan pada infrastruktur pengelolaan sampah. Limbah berbahaya seperti bahan kimia beracun, limbah elektronik, dan limbah medis memerlukan perlakuan khusus yang mahal dan kompleks. Pembuangan sampah yang tidak terkelola dengan baik dapat menyebabkan pencemaran tanah, air, dan udara, serta merusak ekosistem dan kesehatan manusia.
Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan inovasi dan solusi yang efektif dalam pengelolaan limbah. Salah satu pendekatan adalah dengan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan limbah, menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat. Dengan demikian, masyarakat menjadi lebih teredukasi tentang pengelolaan limbah dan pada saat yang sama, pihak pemerintah mendapatkan dukungan untuk implementasi kebijakan terkait.
Pemerintah juga perlu mereformasi sistem pengelolaan sampah di tingkat daerah, termasuk penetapan tipping fee yang wajar, peningkatan sistem retribusi sampah, dan edukasi masyarakat. Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang jelas untuk produk sampingan WtE dan pengembangan infrastruktur pengawasan lingkungan juga menjadi prioritas. Selain itu, penerapan kebijakan Feed-in Tariff (FiT) untuk harga jual listrik dari WtE dapat menarik minat investor.
Dalam konteks hilirisasi nikel, ada beberapa tantangan utama untuk mencapai ekonomi hijau, seperti ketergantungan pada energi fosil. Saat ini, banyak fasilitas pengolahan nikel di Indonesia menggunakan pembangkit listrik berbasis batubara untuk memenuhi kebutuhan energinya. Hal ini tidak hanya meningkatkan emisi karbon, tetapi juga menimbulkan risiko jangka panjang bagi lingkungan.